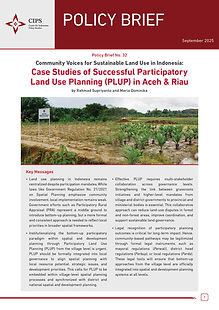Mewujudkan Otonomi Sekolah untuk Mendukung Pembelajaran yang Responsif terhadap Budaya: Bukti dari Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur

Penulis

Sharfina Indrayadi

Riyandi Saras Anggita
Keberagaman sosial, budaya, dan geografis di Indonesia menuntut adanya sistem pendidikan yang terdesentralisasi, yang telah diterapkan sejak akhir 1990-an. Melalui desentralisasi ini, sekolah memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan praktik pembelajaran dengan konteks lokal, dengan menekankan pembelajaran yang responsif terhadap budaya (culturally responsive learning atau CRL) guna mengakomodasi bahasa dan latar belakang budaya siswa yang beragam.
Otonomi sekolah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20/2003 serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 47/2023, memberikan kewenangan dan fleksibilitas bagi sekolah dalam hal pengembangan kurikulum, pengelolaan guru, serta keterlibatan masyarakat. Hal ini memastikan agar pendidikan tetap inklusif dan relevan dengan konteks lokal. Kebijakan seperti Kurikulum Merdeka turut mendukung penerapan CRL dengan memberikan ruang bagi kebijakan daerah untuk mengadaptasi pembelajaran berbasis konteks lokal dalam kegiatan kurikuler maupun kokurikuler. Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan ini dengan mengembangkan regulasi yang mengatur muatan lokal, pendekatan pengajaran, bahan ajar, serta strategi pelaksanaannya.
Akan tetapi, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas guru, infrastruktur yang belum memadai, serta kesulitan dalam menyeimbangkan standar kurikulum nasional dengan adaptasi lokal. Meski CRL menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk pendidikan inklusif, efektivitasnya sangat bergantung kepada kepemimpinan sekolah yang kuat, kolaborasi dengan masyarakat, serta alokasi sumber daya yang mencukupi agar dapat diterapkan secara optimal di berbagai daerah.
Konteks lokal lebih tecermin dalam kebijakan di tingkat daerah. Sebagai contoh, sekolah-sekolah di Jawa dan luar Jawa, yang memiliki perbedaan geografis dan sosial-ekonomi, menerapkan otonomi dengan cara yang berbeda-beda dalam mengadaptasi CRL. Studi kasus di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap adanya perbedaan signifikan dalam kerangka kebijakan yang mengatur implementasi CRL di dua daerah tersebut. Kebijakan di Jawa Timur berfokus pada kerangka pembelajaran adaptif yang lebih luas, dengan mengintegrasikan teknologi dan pendidikan inklusif sekaligus menekankan penggunaan materi yang relevan secara budaya, metode pengajaran berbasis konteks lokal, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, NTT lebih mengutamakan pembelajaran yang responsif terhadap budaya dengan menitikberatkan penggunaan bahasa daerah sebagai sarana peningkatan literasi. Perbedaan ini menciptakan variasi dalam tingkat otonomi sekolah, khususnya pada tiga aspek utama: pendekatan pengajaran (pedagogi) yang responsif terhadap budaya, integrasi konteks lokal ke dalam materi ajar, dan pembelajaran berbasis proyek yang relevan secara budaya.
Keefektifan CRL di tingkat daerah sangat bergantung kepada dua faktor utama yang mendukung otonomi sekolah dalam mengintegrasikan pendekatan ini. Pertama, penguatan program pelatihan guru secara informal, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG), dapat menjadi pendekatan yang lebih hemat biaya dan tepat sasaran untuk mengintegrasikan muatan lokal serta membuat pembelajaran lebih relevan dengan kearifan setempat.

Yulia Esti Utami